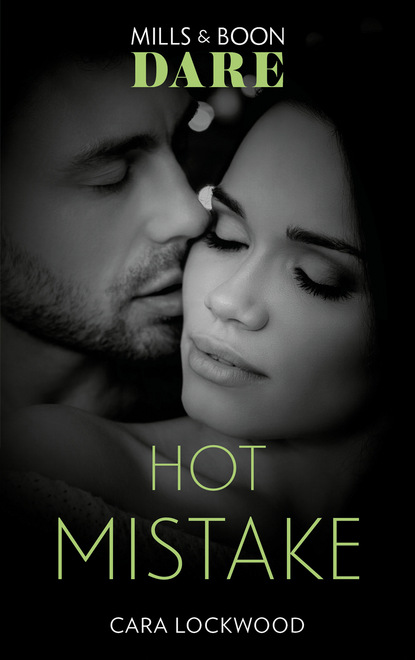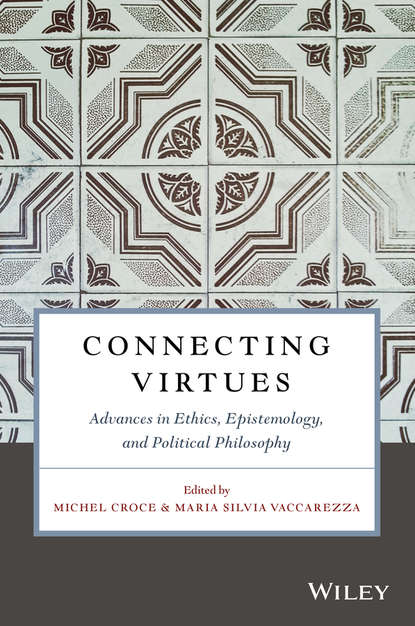Penjelmaan

- -
- 100%
- +
Caitlin nyaris tidak makan, sebuah muak hari pertama yang samar masih menghinggapinya. Ia mencoba merubah rentetan pikirannya. Ia menutup matanya. Ia memikirkan apartemen barunya, naik lima lantai dalam sebuah bangunan dekil di jalan no. 132. Rasa mualnya semakin parah. Ia menarik napas dalam-dalam, menyuruh dirinya untuk berfokus pada sesuatu, sesuatu yang bagus dalam hidupnya.
Adik laki-lakinya. Sam. 14, akan menjadi 20. Sam tidak pernah terlihat ingat bahwa dia adalah adiknya: dia selalu bertingkah seperti kakak laki-lakinya. Dia tumbuh tabah dan kuat dari semua kepindahan, dari kepergian Ayah mereka, dari cara Ibu mereka memperlakukan mereka berdua. Ia bisa melihat hal itu semakin mendekati dia dan bisa melihat bahwa dia mulai menutup dirinya. Seringnya perkelahian sekolah dia tidaklah mengejutkannya. Ia takut itu hanya akan menjadi lebih buruk.
Tapi ketika berhubungan dengan Caitlin, Sam sangat menyayanginya. Dan ia juga menyayanginya. Dia adalah satu-satunya hal yang kosntan dalam hidupnya, satu-satunya yang bisa ia andalkan. Dia nampaknya menguasai satu titik lembut yang tersisa dalam dunianya. Ia bertekad melakukan yang terbaik untuk melindungi dia.
“Caitlin?”
Ia terlompat.
Berdiri di depannya, dengan baki di satu tangan dan kotak biola di tangan lainnya, adalah Jonah.
"Bolehkah aku bergabung denganmu?"
"Ya - maksudku tidak," katanya, salah tingkah.
Bodoh, pikirnya. Berhentilah bertingkah begitu gugup.
Jonah menyunggingkan senyumnya, lalu duduk di depan Caitlin. Dia duduk tegak, dengan postur tubuh yang sempurna, dan meletakkan biolanya dengan hati-hati di sisinya. Dia meletakkan makanannya dengan perlahan. Ada sesuatu tentang dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Dia berbeda dari siapa pun yang pernah is jumpai. Sepertinya dia berasal dari jaman yang berbeda. Dia benar-benar tidak berasal di tempat ini.
"Bagaimana hari pertamamu?" tanya Jonah.
"Tidak seperti yang kuharapkan."
"Aku tahu apa yang kamu maksud," kata Jonah.
"Apakah itu sebuah biola?"
Ia mengangguk pada instrumennya. Dia tetap menutupnya, dan tetap meletakkan satu tangan di atasnya, seolah-olah takut seseorang mungkin mencurinya.
"Ini sebenarnya adalah biola alto. Ini hanya sedikit lebih besar, tapi suaranya sangat berbeda. Lebih mellow."
Ia tidak pernah melihat sebuah biola alto, dan berharap dia akan meletakkannya di meja dan menunjukkan padanya. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, dan ia tidak ingin mengungkitnya. Ia masih meletakkan tangan di atasnya, dan dia nampaknya melindungi benda itu, seperti layaknya benda yang personal dan pribadi.
"Apakah kau sering berlatih?"
Jonah mengangkat bahu. "Beberapa jam sehari," jawabnya sambil lalu.
"Beberapa jam!? Kau pasti hebat!"
Dia mengangkat bahu lagi. "Aku oke, sepertinya. Ada banyak pemain biola yang sangat lebih bagus dariku. Tapi aku berharap ini adalah tiketku untuk keluar dari tempat ini."
"Aku selalu ingin bermain piani," kata Caitlin.
"Kenapa tidak?"
Ia akan berkata, aku tidak pernah punya piano, tapi ia menghentikan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia mengangkat bahu dan kembali pada makanannya.
"Kau tidak perlu memiliki sebuah piano," kata Jonah.
Ia mendongak, terkejut bahwa ia dapat membaca pikirannya.
"Ada ruang latihan di sekolah ini. Untuk semua hal jelek yang ada di sini, paling tidak itulah hal baiknya. Mereka akan memberimu pelajaran dengan gratis. Yang perlu kau lakukan hanya mendaftar."
Mata Caitlin melebar.
"Sungguh?"
"Ada lembar pendaftaran di luar ruang musik. Mintalah bertemu Ibu Lennox. Katakan pada beliau kau adalah temanku."
Teman. Caitlin menyukai bunyi kata itu. Ia perlahan-lahan merasakan suatu kegemburaan yang muncul di dalam dirinya.
Ia tersenyum lebar. Mata mereka bertemu selama sekejap.
Kembali memandangi mata hijaunya yang bercahaya, ia terbakar oleh keinginan untuk menanyakan jutaan pertanyaan: Apa kau punya pacar? Mengapa kau sangat baik? Apa kau benar-benar menyukaiku?
Tapi, sebaliknya, ia menggigit lidahnya dan tidak mengatakan apapun.
Takut bahwa waktu mereka bersama akan segera habis, ia memindai otaknya atas sesuatu untuk ditanyakan pada dia yang akan memperpanjang percakapan mereka. Ia mencoba untuk memikirkan sesuatu yang akan memastikan bahwa ia akan dapat menemuinya lagi. Tapi ia merasa gugup dan membeku.
Ia akhirnya membuka mulutnya, dan ketika ia melakukannya, lonceng berdentang.
Ruangan itu meledak menjadi riuh dan bergerak, dan Jonah berdiri, meraih biola altonya.
"Aku terlambat," katanya, meraih bakinya.
Dia melihat ke arah baki Caitlin. "Bolehkah aku membawa bakimu?"
Ia menunduk, menyadari bahwa ia melupakannya, dan menganggukkan kepalanya.
"Oke," kata Jonah.
Ia berdiri di sana, tiba-tiba malu, tidak tahu apa yang harus dikatakan.
"Hmm...sampai ketemu lagi."
"Sampai ketemu lagi," jawab Caitlin dengan lemah, suaranya hampir-hampir menyeruapi bisikan.
*
Hari pertama sekolah selesai, Caitlin keluar dari bangunan itu menuju ke siang hari bulan Maret yang cerah. Meskipun bertiup angin kencang, ia tidak lagi merasa dingin. Meskipun semua remaja di sekelilingnya berteriak ketika mereka mengalir keluar, ia tidak lagi merasa terganggu oleh kebisingan itu. Ia merasa hidup, dan bebas. Sisa hari itu telah berjalan secara samar-samar; ia bahkan tidak bisa mengingat satu saja nama guru baru.
Ia tidak dapat berhenti memikirkan Jonah.
Ia bertanya-tanya apakah ia telah bertingkah seperti orang bodoh di kafetaria itu. Ia telah tersandung oleh kata-katanya; ia bahkan nyaris tidak menanyakan apapun. Yang bisa ia pikirkan hanya menanyakan tentang biola altonya yang bodoh. Ia harusnya menanyakan di mana dia tinggal, dari mana dia berasal, ke mana dia mendaftar kuliah.
Yang paling penting, apakah dia memiliki seorang pacar. Seseorang seperti dia seharusnya mengencani seseorang.
Tepat pada saat itu, seorang remaja perempuan Hispanik cantik yang berpakaian dengan bagus tersenggol olah Caitlin. Caitlin memandanginya dari atas ke bawah ketika ia lewat, dan bertanya-tanya selama sedetik apakah itu adalah pacarnya.
Caitlin berbelok ke jalan no. 134, dan selama sedetik, melupakan ke mana ia akan pergi. Ia tidak pernah berjalan kaki pulang dari sekolah sebelumnya, dan selama beberapa saat, ia sama sekali tupa di mana apartemen barunya. Ia berdiri di sana di pojokan, bingung. Sebuah awan menutupi matahari dan angin kencang berhembus, dan ia tiba-tiba merasa dingin lagi.
"Hei, amiga!"
Caitlin berbalik, dan menyadari ia berdiri di depan kios dekil di pojokan. Empat pria lusuh duduk di kursi plastik di depannya, tampaknya tidak menyadari hawa dingin, menyeringai pada Caitlin seolah-olah ia adalah santapan selanjutnya.
"Ayo ke sini, sayang!" teriak yang lainnya.
Ia ingat.
Jalan no. 132. Itu dia.
Ia berbelok dengan cepat dan berjalan dengan cepat menyusuri sisi jalan lainnya. Ia memeriksa di belakang bahunya beberapa kali untuk melihat apakah pria-pria itu mengikutinya. Untungnya, tidak.
Angin dingin menyengat pipinya dan menyadarkannya, ketika kenyataan kejam terhadap lingkungan sekitarnya mulai tenggelam. Ia memandang sekeliling pada mobil-mobil yang ditinggalkan, dinding-dinding bergrafiti, kawat berduri, bar-bar di semua jendela, dan ia tiba-tiba merasa sendirian. Dan sangat takut.
Hanya tinggal 3 blok lagi menuju apartemennya, tapi lamanya terasa seperti seumur hidupnya. Ia berharap ia memiliki teman di sisinya - lebih baik lagi, Jonah - dan ia bertanya-tanya apakah ia bisa menjalani perjalanan ini sendirian setiap hari. Sekali lagi, ia merasa kesal pada Ibunya. Bagaimana bisa dia selalu memindahkannya, selalu menempatkan Caitlin di tempat baru yang ia benci? Kapankah hal itu akan berakhir?
Ada kaca pecah.
Jantung Caitlin berdegup lebih cepat ketika ia melihat sejumlah aktivitas jauh di sebelah kiri, di sisi lain jalan itu. Ia berjalan dengan cepat dan mencoba untuk tetap menundukkan kepalanya, tapi saat ia semakin dekat, ia mendengar teriakan dan tawa aneh, dan ia tidak menahan untuk memperhatikan apa yang terjadi.
Empat remaja bertubuh besar - 18 atau 19, mungkin - berdiri di depan remaja lain. Dua dari mereka memegang tangannya, sementara yang ketiga melangkah maju dan meninju perutnya, dan yang keempat melangkah maju dan meninju wajahnya. Remaja itu, mungkin 17 tahun, tinggi, kurus dan tanpa pertahanan, jatuh ke tanah. Kedua remaja laki-laki melangkah ke depan dan menendang wajahnya.
Meskipun sendirian, Caitlin berhenti dan melihatnya. Ia merasa ngeri. Ia tidak pernah melihat hal seperti itu.
Kedua remaja lain mengambil beberapa langkah di sekitar korban mereka, lalu mengangkat sepatu boot mereka tinggi-tinggi dan menendangkannya.
Caitlin takut mereka akan menendang anak itu sampai mati.
"TIDAK!" teriaknya.
Ada suara berderak kesakitan ketika mereka menendangkan kakinya.
Tapi itu bukanlah suara tulang yang patah - melainkan, itu adalah suara kayu. Kayu yang hancur. Caitlin melihat bahwa mereka menginjak-injak sebuah alat musik kecil. Ia melihat lebih dekat, dan melihat potongan dan serpihan sebuah biola alto bercecer di trotoar.
Ia mengangkat tangan ke arah mulutnya dengan perasaan ngeri.
“Jonah!?”
Tanpa berpikir, Caitlin menyebrangi jalan itu, menuju sekumpulan laki-laki, yang sekarang mulai memperhatikannya. Mereka memandanginya dan mata jahat mereka melebar sembari menyikut satu sama lain.
Ia berjalan langsung ke arah korban dan melihat bahwa itu memang Jonah. Wajahnya berdarah dan memar, dan ia pingsan.
Ia memandangi sekumpulan remaja laki-laki itu, kemaharannya mengalahkan ketakutannya, dan berdiri di antara Jonah dan mereka.
"Biarkan dia!" teriaknya pada kelompok remaja itu.
Remaja yang di tengah, paling tidak 64, berotot, membalas dengan tertawa.
"Atau apa?" tanya dia, suaranya sangat dalam.
Caitlin merasakan dunia berlalu cepat, dan menyadari bahwa ia baru saja didorong dengan keras dari belakang. Ia menaikkan sikutnya ketika ia menabrak beton, tapi itu hampir tidak melindungi tabrakannya. Di sudut matanya, ia bisa melihat buku hariannya melayang, kertas-kertasnya berhamburan ke mana-mana.
Ia mendengar tawa. Dan kemudian langkah-langkah kaki, datang ke arahnya.
Jantungnya berdegup dalam dadanya, adrenalinnya muncul. Ia berhasil bergulung dan bersusah-payah berdiri sebelum mereka mencapainya. Ia mengambil langkah seribu di jalan kecil itu, berlari menyelamatkan diri.
Mereka mengikuti di belakangnya.
Di salah satu dari beberapa sekolahnya, kembali Caitlin mengingat bahwa ia akan mempunyai masa depan panjang di suatu tempat, ia mengikuti olahraga lari, dan menyadari ia bagus dalam bidang itu. Yang terbaik dalam tim, sebenarnya. Tidak dalam jarak jauh, tapi dalam lari cepat 100 yard. Ia bahkan bisa berlari lebih cepat dari sebagian besar laki-laki. Dan sekarang, hal itu kembali menyelimutinya.
Ia berlari menyelamatkan hidupnya, dan para laki-laki itu tidak dapat menangkapnya.
Caitlin melirik ke belakang dan melihat seberapa jauhnya mereka di belakang, dan merasa optimis bahwa ia bisa kabur dari mereka semua. Ia hanya harus melakukan belokan yang tepat.
Jalan kecil itu berakhir di sebuah T, dan ia bisa berbelok ke kiri maupun kanan. Ia tidak akan mempunyai waktu untuk merubah keputusannya jika ia ingin mempertahankan kemenangannya, dan ia harus memilih dengan cepat. Ia tidak dapat melihat apa yang ada di sekitar tiap pojokan, sekalipun. Dengan membabi buta, ia berbelok ke kiri.
Ia berdoa semoga itu adalah pilihan yang benar. Ayolah. Kumohon!
Jantungnya berhenti ketika ia melakukan belokan tajam ke kiri dan melihat jalan buntu di depannya.
Salah jalan.
Jalan buntu. Ia berlari ke arah dinding, mencari-cari jalan keluar, apapun itu. Menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, ia berbalik untuk menghadapi para penyerang yang mendekatinya.
Terengah-engah, ia menyaksikan mereka berbelok dan mendekat. Ia bisa melihat di belakang bahu mereka bahwa jika ia berbelok ke kanan, ia akan dapat pulang dengan bebas. Tentu saja. Hanya keberuntungan.
"Baiklah, cewek," salah satu dari merka berkata, "kau akan menderita sekarang."
Menyadari bahwa ia tidak mempunyai jalan keluar, mereka berjalan perlahan-lahan ke arahnya, terengah-engah, menyeringai, dan menikmati kekerasan yang akan datang.
Caitlin menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menyakinkan Jonah untuk bangun, muncul di pojokan, terjaga dan penuh tenaga, siap untuk menyelamatkannya. Tapi ia membuka matanya dan dia tidak ada di sana. Hanya para penyerangnya. Semakin mendekat.
Ia membayangkan Ibunya, bagaimana ia membencinya, dari semua tempat yang sudah dia paksakan untuk hidup. Ia memikirkan adiknya Sam. Ia memikirkan bagaimana hidupnya setelah hari ini.
Ia memikirkan seluruh hidupnya, tentang bagaimana ia selama ini diperlakukan, tentang bagaimana tidak seorang pun yang memahami dirinya, tentang bagaimana tidak sesuatu pun menjadi seperti keinginannya. Dan sesuatu berdetak. Entah bagaimana, ia merasa sudah cukup.
Aku tidak layak menerima ini. Aku TIDAK layak menerima ini.
Dan kemudian, tiba-tiba, ia merasakannya.
Itu adalah sebuah gelombang, sesuatu yang tidak seperti apapun yang pernah ia alami. Itu adalah sebuah gelombang kemurkaan, meluap dalam dirinya, membanjiri darahnya. Gelombang itu berpusat dalam perutnya, dan menyebar dari sana. Ia bisa merasakan kakinya menjejak tanah, seolah-olah ia dan beton itu adalah satu, dan bisa merasakan kekuatan terpenting melandanya, merayap melalui pinggangnya, naik ke lengannya, menuju bahunya.
Caitlin mengeluarkan raungan yang mengejutkan dan menakutkan juga bagi dirinya. Ketika remaja pertama mendekatinya dan mendaratkan tangan gempalnya ke pergelangan tangannya, ia menyaksikan tangannya bergerak dengan sendirinya, mencengkram kuat pergelangan tangan penyerangnya dan memutarnya ke belakang pada sudut yang tepat. Wajah remaja itu berkerut terkejut ketika pergelangannya, dan kemudian lengannya, patah menjadi dua.
Dia jatuh berlutut, menjerit.
Ketiga remaja laki-laki lain membelalak dengan terkejut.
Yang bertubuh paling besar dari ketiganya menyerang ke arahnya.
"Kau sia-"
Sebelum dia bisa menyelesaikan, ia lompat ke udara dan menanamkan kedua kakinya tepat di dadanya, mengirimnya terbang ke belakang sekitar sepuluh kaki dan menabrak tumpukan kaleng sampah logam.
Ia terbaring di sana, tidak bergerak.
Kedua remaja lainnya saling memandang, terkejut. Dan sangat ketakutan.
Caitlin melangkah maju, merasakan aliran kekuatan yang tidak manusiawi menjalarinya, dan mendengar dirinya menggeram ketika ia menangkap kedua remaja (masing-masing berukuran dua kali darinya), mengangkat masing-masing dari mereka beberapa kaki di atas tanah menggunakan satu tangan.
Ketika mereka tergantung di udara, ia mengayunkan mereka kembali, lalu mengayunkan mereka bersama-sama, menubrukkan mereka berdua satu sama lain dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka berdua jatuh ke tanah.
Caitlin berdiri di sana, bernapas, berbuih dengan kemurkaan.
Semua keempat remaja itu tidak bergerak.
Ia tidak merasa lega. Sebaliknya, ia menginginkan lagi. Lebih banyak remaja untuk dilawan. Lebih banyak tubuh untuk dilempar.
Dan ia menginginkan sesuatu yang lain.
Ia tiba-tiba memiliki pandangan sejernih kristal, dan dapat menyoroti leher mereka, terpajan. Ia bisa melihat sampai dengan sepersepuluh inci, dan ia dapat melihat, dari tempatnya berdiri, pembuluh darah berdenyut pada masing-masing leher itu. Ia ingin menggigit. Untuk makan.
Tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya, ia menggoyangkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan pekikan tidak wajar, bergema pada bangunan dan blok itu. Itu adalah pekikan kemenangan, dan kemarahan yang tidak terpenuhi.
Itu adalah jeritan hewan yang menginginkan lebih banyak.
Bab Dua
Caitlin berdiri di depan pintu apartemen barunya, memandangi, dan tiba-tiba menyadari di mana ia berada. Ia tidak tahu bagaimana ia sampai di sana. Hal terakhir yang ia ingat, ia ada dalam gang. Entah bagaimana, ia bisa kembali pulang.
Ia ingat, bagaimana pun, setiap detik atas apa yang terjadi dalam gang itu. Ia mencoba untuk menghapusnya dari pikirannya, tapi tidak bisa. Ia menatap lengan dan tangannya, mengharapkannya terlihat berbeda - tapi lengan dan tangannya normal. Hanya seperti yang selalu mereka lakukan. Kemarahan merayap melalui dirinya, merubahnya, lalu pergi dengan seketika.
Tapi efek setelahnya yang tersisa: ia merasa hampa, untuk satu hal. Mati rasa. Dan ia merasakan sesuatu hal lain. Ia tidak dapat memahaminya dengan benar. Gambar-gambar bermunculan melalui benaknya, gambar-gambar leher para pengganggu itu. Dari detak jantung mereka. Dan ia merasa kelaparan. Sebuah hasrat.
Caitlin sangat tidak ingin pulang. Ia tidak ingin berurusan dengan Ibunya, khususnya hari ini, tidak ingin berurusan dengan tempat baru, dengan tidak berkemas. Jika itu tidak karena Sam beradd di sana, ia mungkin telah berpaling dan pergi. Ke mana ia akan pergi, ia tidak ada gagasan - tapi paling tidak ia akan berjalan.
Ia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan serta meletakkan tangannya di pegangan pintu. Entah kenapa pegangan pintu itu hangat, atau tangannya yang sedingin es.
Caitlin memasuki apartemen yang terlalu terang itu. Ia bisa mencium bau makanan di atas kompor - atau mungkin, dalam microwave. Sam. Ia selalu pulang lebih cepat dan membuat makanan untuk dirinya sendiri. Ibunya tidak akan pulang selama berjam-jam.
"Itu tidak terlihat seperti hari pertama yang bagus."
Caitlin berbalik, terkejut pada suara Ibunya. Dia duduk di sana, di sofa, mengisap sebuah rokok, telah mengamati Caitlin dan mencibir.
"Apa yang kau lakukan, sudah merusak sweater itu?
Caitlin melihat ke bawah dan menyadari untuk pertama kalinya ada noda; mungkin akibat menabrak semen.
"Kenapa ibu ada di rumah lebih awal?" tanya Caitlin.
"Hari pertama bagiku, juga, tahu kan," tukasnya. "Kau bukan satu-satunya. Pekerjaan ringan. Bos menyuruhku pulang lebih awal."
Caitlin tidak tahan dengan nada nakal Ibunya. Tidak malam ini. Ia menghina kepadanya, dan malam ini, Caitlin merasa muak. Ia memutuskan untuk memberinya rasa obat-obatannya sendiri.
"Bagus," balas Caitlin. "Apa itu berarti kita pindah lagi?"
Ibunya tiba-tiba melompat berdiri. "Berhati-hatilah dengan ucapanmu itu!" teriaknya.
Caitlin tahu Ibunya sudah menunggu sebuah alasan untuk berteriak padanya. Ia pikir itu cara terbaik hanya untuk memancingnya dan segera menyelesaikannya.
"Kau seharusnya tidak merokok di depan Sam," jawab Caitlin dingin, lalu memasuki kamar tidur kecilnya dan membanting pintu di belakangnya, menguncinya.
Segera, Ibunya menggedor pintu.
"Kau keluar ke sini, anak sialan! Cara bicara semacam apa kepada ibumu!? Siapa yang menaruh roti di mejamu...."
Pada malam ini, Caitlin, perhatiannya sangat teralihkan, bisa meredam suara Ibunya. Sebaliknya, ia memutar ulang benaknya atas peristiwa hari itu. Suara-suara tawa remaja laki-laki itu. Suara detak jantungnya sendiri di telinganya. Suara raungannya sendiri.
Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ia mendapatkan kekuatan semacam itu? Apakah itu hanya dorongan adrenalin saja? Suatu bagian dari dirinya berharap demikian. Tapi bagian lain dari dirinya tahu itu bukan seperti itu. Apakah sebenarnya?
Gedoran di pintu berlanjut, tapi Caitlin hampir tidak mendengarnya. Ponselnya ada di mejanya, bergetar dengan gilanya, menyala-nyala dengan Pesan Instan, SMS, email, obrolan Facebook - tapi ia hampir tidak bisa mendengarnya juga.
Ia menggerakkan jendela kecilnya dan melihat ke bawah ke Amsterdam Ave, dan suara baru muncul dalam benakmya. Itu adalah bunyi suara Jonah. Gambaran senyumnya. Suara yang rendah, dalam dan menenangkan. Ia mengingat bagaimana lembutnya dia, bagaimana rapuhnya dia. Lalu ia melihatnya terbaring di tanah, berlumuran darah, alat musik berharganya hancur. Sebuah gelombang kemarahan baru muncul.
Kemarahannya berubah menjadi kekhawatiran - khawatir apakah dia baik-baik saja, apakah dia pergi, apakah dia berhasil pulang. Ia membayangkan dirinya memanggilnya. Caitlin. Caitlin.
“Caitlin?”
Sebuah suara baru dari luar pintunya. Suara seorang anak laki-laki.
Bingung, ia menyentaknya.
"Aku Sam. Biarkan aku masuk."
Ia menuju pintunya dan menyandarkan kepala di depannya.
"Mama pergi," kata suara di sisi lain. "Keluar untuk beli rokok. Ayolah, biarkan aku masuk."
Ia membuka pintu.
Sam berdiri di sana, menatap kembali, kekhawatiran terukir di wajahnya. Pada usia 15 tahun, dia terlihat lebih tua dari usianya. Ia tumbuh lebih awal, hampir enam kaki, tetapi dia tidak berisi, dan dia kikuk dan kurus. Dengan rambut hitam dan mata coklat, warnanya mirip dengan miliknya. Mereka benar-benar terlihat istimewa. Ia bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Dia menyayanginya lebih dari segalanya.
Ia membiarkannya masuk, dengan segera menutup pintu di belakangnya.
"Maaf," katanya. "Aku hanya tidak bisa menghadapinya malam ini."
"Apa yang terjadi dengan kalian berdua?"
"Seperti biasanya. Dia menungguku pada saat aku masuk."
"Aku rasa dia baru saja mengalami hari yang sulit," kata Sam, mencoba membuat kedamaian di antara mereka, seperti biasanya. "Kuharap mereka tidak memecatnya lagi.
"Siapa peduli? New York, Arizona, Texas… Siapa yang peduli apa selanjutnya? Kepindahan kita tidak akan pernah berakhir."
Sam mengerutkan kening saat dia duduk di kursi mejanya, dan ia segera merasa bersalah. Ia kadang-kadang memiliki lidah yang tajam, berbicara tanpa berpikir, dan ia berpikir dapat menariknya kembali.
"Bagaimana hari pertamamu?" tanyanya, mencoba mengubah topik pembicaraan.
Dia mengangkat bahu. "Oke, kayaknya." Dia mengunci kursi dengan kakinya.
Dia mendongak. "Kau?"
Ia mengangkat bahu. Pasti ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya, karena Sam tidak berpaling. Dia tetap menatapnya.
"Apa yang terjadi?"
"Tidak ada," katanya membela diri, dan berpaling lalu berjalan ke arah jendela.
Ia bisa merasakan dia mengamatinya.
"Kau terlihat...berbeda."
Ia berhenti sejenak, bertanya-tanya apakah dia tahu, bertanya-tanya apakah tampang luarnya menunjukkan perubahan. Ia menelan ludah.
"Gimana?"
Diam.
"Aku tidak tahu," dia akhirnya menjawab.
Ia memandang ke luar jendela, mengamati tanpa tujuan ketika seorang pria di luar pojok bodega menjatuhkan kantung uang seorang pembeli.
"Aku benci tempat baru ini," katanya.
Ia berbalik dan menghadap dia.
"Aku juga begitu."
"Aku bahkan berpikiran tentang..." dia menundukkan kepalanya, "...pergi."
"Apa maksudmu?"
Dia mengangkat bahu.
Ia menatap Sam. Dia terlihat benar-benar depresi.
"Ke mana?" tanyanya.
"Mungkin...mencari Ayah."
"Bagaimana caranya? Kita tidak ada ide di mana dia."
"Aku bisa mencoba. Aku bisa menemukannya."
"Bagaimana caranya?"
"Aku tidak tahu.... Tapi aku bisa mencoba."
"Sam. Ia mungkin meninggal sepanjang pengetahuan kita."
"Jangan bilang begitu!" teriaknya, dan wajahnya berubah merah menyala.
"Maaf," katanya.
Ia kembali tenang.
"Tapi apakah kau pernah mempertimbangkan bahwa, bahkan jika kita menemukan dia, dia mungkin sama sekali tidak ingin menemuai kita? Selain itu, dia pergi. Dan dia tidak pernah mencoba menghubungi kita."
"Mungkin karena Ibu tidak mengizinkan dia melakukannya."
"Atau mungkin karena dia tidak menyukai kita."
Kerutan Sam semakin dalam ketika ia memainkan jari kaki ke lantai lagi. "Aku mencarinya di Facebook."
Mata Caitlin terbuka lebar karena terkejut.
"Kau menemukannya?"
"Aku tidak yakin. Ada 4 orang dengan namanya. 2 dari mereka adalah pribadi dan tidak ada foto. Aku mengirimi mereka berdua sebuah pesan."